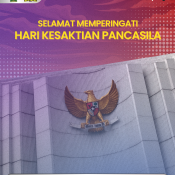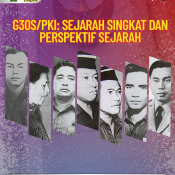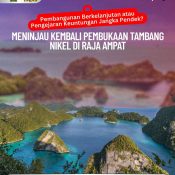Hari Kesaktian Pancasila
Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penetapannya tidak lepas dari tragedi politik 1965, ketika Gerakan 30 September (G30S) yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini mengguncang politik nasional, mengubah arah pemerintahan, dan membuka jalan bagi lahirnya rezim Orde Baru. Melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, menegaskan bahwa dasar negara tetap tegak menghadapi ancaman ideologi lain.
Dalam narasi Orde Baru, istilah “kesaktian” dipakai untuk menekankan bahwa Pancasila seolah memiliki kekuatan luar biasa, bahkan supranatural, karena mampu bertahan dari ancaman kudeta. Peringatan ini kemudian dimanfaatkan sebagai legitimasi politik: militer diposisikan sebagai penyelamat bangsa, sementara komunisme dicitrakan sebagai musuh utama. Upacara besar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, lengkap dengan ikrar kesetiaan pada Pancasila, menjadi ritual tahunan yang sarat muatan simbolis. Bahkan melalui film “Pengkhianatan G30S/PKI” (1984), rezim menanamkan narasi tunggal tentang peristiwa 1965, membentuk ingatan kolektif generasi muda.
Pasca reformasi 1998, makna Hari Kesaktian Pancasila mulai diperdebatkan. Banyak sejarawan dan aktivis HAM menilai bahwa peringatan ini lebih banyak mencerminkan propaganda politik ketimbang realitas sejarah. Kritik diarahkan pada praktik Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan untuk membungkam oposisi, alih-alih menjalankan nilai-nilainya seperti demokrasi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, hingga kini peringatan tetap dilaksanakan, meski lebih sederhana, dengan penekanan pada refleksi pentingnya Pancasila menghadapi tantangan zaman.
Perlu diingat, sejarah Pancasila memiliki dua tanggal penting. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila—saat Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI 1945—sementara 1 Oktober menegaskan bahwa Pancasila mampu bertahan dari krisis pasca G30S. Keduanya saling melengkapi: kelahiran ideologi negara dan ketahanannya dalam menghadapi ancaman.
Dalam konteks kekinian, tantangan terhadap Pancasila berbeda dari masa lalu. Ancaman komunisme tidak lagi dominan, tetapi muncul persoalan baru seperti radikalisme, intoleransi, korupsi, kesenjangan sosial, dan melemahnya rasa kebangsaan. Pancasila hanya akan benar-benar “sakti” bila dijalankan dalam praktik: menegakkan keadilan, menghargai keberagaman, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun demokrasi yang sehat.
Bagi mahasiswa, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak dipahami semata sebagai peringatan historis, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis. Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah Pancasila hari ini benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara, atau sekadar dijadikan slogan retoris? Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam gerakan sosial, akademik, maupun advokasi kebijakan publik.
Momentum 1 Oktober dapat menjadi ajakan bagi mahasiswa untuk menggali esensi Pancasila sebagai landasan etis, mengkritisi praktik bernegara yang menjauh dari nilai-nilainya, sekaligus mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya ritual mengenang masa lalu, melainkan kompas moral untuk membangun bangsa yang adil, demokratis, makmur, dan berdaulat.