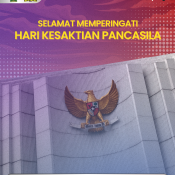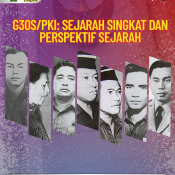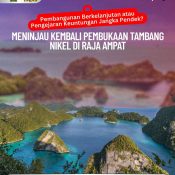RUU KUHAP: ARAH PEMBARUAN ATAU ANCAMAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA?
RUU KUHAP: ARAH PEMBARUAN ATAU ANCAMAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA?
Sejak diundangkannya Undang‐Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Indonesia telah memiliki aturan hukum acara pidana yang lebih modern
dibandingkan dengan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) warisan kolonial Belanda. KUHAP
1981 dipuji sebagai kemajuan karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki hukum acara
pidana yang mengedepankan hak tersangka dan terdakwa. Namun, perjalanan waktu
menunjukkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah banyak menghadapi tantangan.
Dinamika masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan teknologi, serta munculnya
berbagai bentuk kejahatan baru membuat banyak pasal dalam KUHAP lama dianggap tidak
lagi relevan.
Seiring dengan itu, berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam
proses peradilan pidana juga terus terjadi. Tersangka kerap mengalami penyiksaan saat
pemeriksaan, hak akses bantuan hukum sering diabaikan, dan ada banyak kasus penahanan
yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR memandang perlu
melakukan pembaruan menyeluruh melalui Rancangan Undang‐Undang Kitab
Undang‐Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembahasan ini menjadi momen
penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat luas,
sekaligus menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman.
Alasan Penyusunan RUU KUHAP
Ada beberapa alasan utama mengapa KUHAP baru diperlukan. Pertama, KUHAP lama
sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman. Banyak persoalan seperti bukti digital, kejahatan
siber, dan penyidikan kasus lintas negara yang tidak diatur secara memadai. Akibatnya, aparat
penegak hukum seringkali mengisi kekosongan hukum dengan kewenangan yang luas, yang
justru berpotensi melanggar HAM.
Kedua, KUHAP baru dibutuhkan untuk memperkuat prinsip due process of law, yaitu
jaminan bahwa proses peradilan berjalan adil, transparan, dan menghormati hak setiap orang.
Dalam KUHAP lama, pengawasan terhadap tindakan aparat seperti penangkapan, penahanan,
dan penyitaan masih lemah. Tidak sedikit kasus salah tangkap atau penahanan tanpa bukti yang
cukup. Melalui RUU KUHAP, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan yudisial
terhadap setiap tindakan aparat agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga, RUU KUHAP juga merupakan jawaban atas berbagai putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal dalam KUHAP lama. Misalnya, MK
pernah membatalkan pasal yang mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan. Dengan
adanya RUU KUHAP, aturan yang sudah dibatalkan MK bisa diperbaiki dan dikodifikasi ulang
agar lebih jelas. Keempat, KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan
pidana terpadu (integrated criminal justice system). RUU KUHAP dirancang untuk
menyatukan peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat
dalam satu kerangka kerja yang saling mendukung.
Perlindungan HAM sebagai Prioritas
1. Pengawasan Yudisial yang Lebih Kuat
Salah satu perubahan penting dalam RUU KUHAP adalah penguatan pengawasan
yudisial. Semua tindakan aparat yang bersifat upaya paksa, seperti penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus mendapat izin atau diawasi oleh
pengadilan. Tujuannya agar tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak
tersangka. Namun, sejumlah pihak menilai mekanisme pengawasan ini masih lemah karena
tidak ada batas waktu yang tegas kapan izin pengadilan harus diberikan dan apa sanksinya
jika aparat melanggar prosedur.
2. Aturan Upaya Paksa yang Lebih Ketat
Dalam KUHAP lama, banyak tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan hanya
berdasarkan diskresi penyidik. RUU KUHAP berupaya memperketat aturan tersebut
dengan mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup sebelum aparat melakukan
upaya paksa. Meskipun demikian, ada kekhawatiran karena istilah “keadaan mendesak”
masih bisa menjadi celah bagi aparat untuk bertindak tanpa izin pengadilan.
3. Saksi Mahkota
Penggunaan saksi mahkota dalam RUU KUHAP juga menjadi sorotan. Jaksa diberikan
kewenangan untuk menunjuk tersangka lain yang perannya lebih ringan sebagai saksi
dalam persidangan. Banyak ahli hukum menilai hal ini berpotensi melanggar prinsip hak
untuk tidak memberatkan diri sendiri (non-self-incrimination). Selain itu, ada risiko
penyidik atau jaksa menggunakan saksi mahkota untuk menekan tersangka yang lain.
4. Standar Pembuktian
RUU KUHAP menetapkan bahwa perkara pidana dapat dilanjutkan jika ada minimal
dua alat bukti yang sah. Namun, standar ini dinilai belum cukup karena tidak
memperhatikan kualitas dan kekuatan bukti. Idealnya, pembuktian harus memenuhi standar
“beyond reasonable doubt” agar tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang benar-
benar kuat.
5. Restorative Justice dan Diversi
RUU KUHAP juga memuat ketentuan mengenai restorative justice, yakni penyelesaian
perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi
yang adil. Namun, pengaturannya dinilai masih lemah. Wewenang untuk menghentikan
perkara melalui diversi justru diberikan kepada penyidik, yang dikhawatirkan dapat
disalahgunakan.
6. Pengaturan Sidang Elektronik
Di era digital, RUU KUHAP seharusnya mengatur secara jelas mengenai sidang
elektronik atau sidang hybrid. Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut masih minim dan
lebih banyak mengandalkan peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya sementara.
Padahal, sidang elektronik terbukti penting, terutama saat pandemi COVID-19 lalu.
RUU KUHAP Belum Menjamin Perlindungan Hak Korban dan Tersangka
Berbagai kalangan memberikan respon yang beragam terhadap RUU KUHAP.
Organisasi masyarakat sipil seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa
RUU KUHAP masih memiliki kelemahan mendasar dalam melindungi hak korban dan
tersangka. Salah satu kritik utama adalah masih lemahnya pengawasan eksternal terhadap
aparat penegak hukum. Ahli hukum seperti Asfinawati (STHI Jentera) juga menilai
penggunaan saksi mahkota dalam RUU KUHAP sebagai kemunduran. Menurutnya, saksi
mahkota berpotensi menimbulkan kriminalisasi karena memberikan insentif kepada tersangka
untuk memberatkan orang lain demi mendapatkan keringanan hukuman. Di sisi lain,
pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa RUU
KUHAP terus diperbaiki dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jaksa Agung
juga optimistis bahwa KUHAP baru akan memperkuat prinsip checks and balances dalam
penegakan hukum.
Harapan untuk KUHAP Baru
RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR saat ini adalah momentum penting untuk
memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. KUHAP baru harus mampu mencegah
penyalahgunaan wewenang, menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum,
serta memberikan posisi yang setara bagi korban kejahatan. Namun, KUHAP baru juga harus
jelas dalam membatasi kewenangan aparat. Celah hukum seperti istilah “keadaan mendesak”
yang tidak dijelaskan secara rinci bisa menjadi pintu masuk pelanggaran HAM. Karena itu,
keterlibatan masyarakat sipil dan pakar hukum dalam pembahasan RUU KUHAP sangat
penting.
Jika disahkan dengan penuh kehati-hatian, KUHAP baru dapat menjadi landasan
penting bagi terciptanya peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Namun,
jika pembahasan dilakukan terburu-buru dan tanpa pengawasan publik, RUU KUHAP bisa saja
menjadi instrumen baru yang justru memperkuat praktik sewenang-wenang.
Kesimpulan
RUU KUHAP adalah bagian penting dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Setelah
lebih dari 40 tahun, hukum acara pidana Indonesia memang membutuhkan pembaruan. Namun,
pembaruan itu harus benar-benar memperkuat prinsip fair trial dan perlindungan hak asasi
manusia.
Pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat sipil,
akademisi, dan praktisi hukum agar KUHAP baru tidak hanya menjadi kosmetik perubahan.
Sebaliknya, KUHAP baru harus menjadi instrumen yang benar-benar mampu membangun
sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menghormati martabat manusia.
KUHAP Baru Harus untuk Rakyat, Bukan untuk Kekuasaan